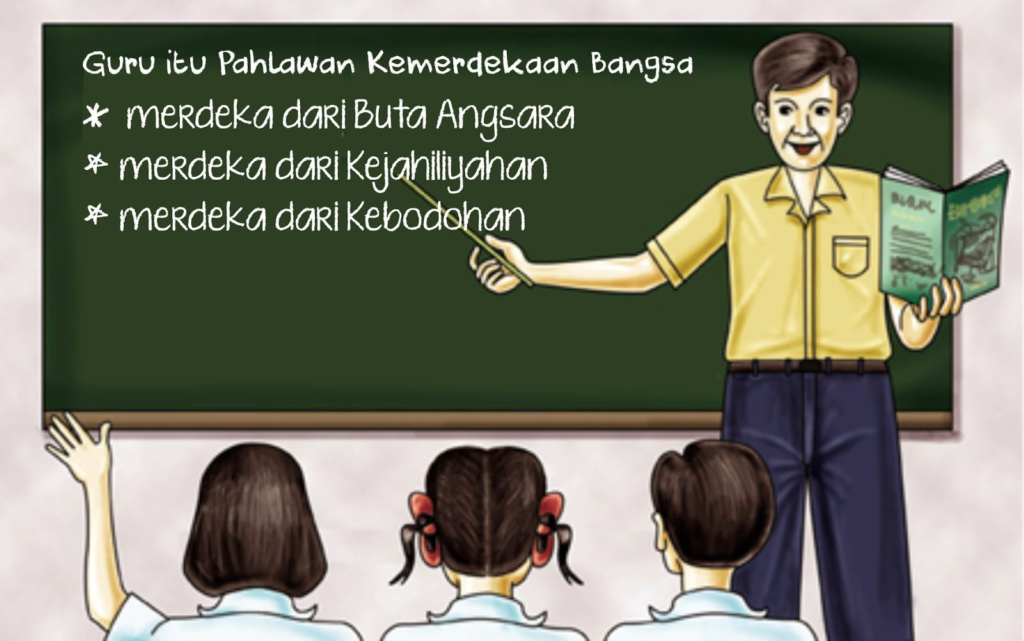Catatan tentang Hari Guru
Oleh: Alfred B. Jogo Ena
“Guru, di manakah Engkau tinggal?”
“Mari dan kamu akan melihatnya.”
Interaksi antara murid dan guru terjadi secara persuasif, tidak intimidatif apalagi agitatif.
Pertanyaan murid mungkin secara faktual berupa rumah tinggal secara fisik. Tetapi jawaban Sang Guru bukanlah melulu soal fisik tetapi soal relasi yang terbangun, soal situasi dua hati yang saling memberi dan menerima.
Ajakan mari dan kamu akan melihatnya justru membuat sang murid merasa nyaman dan dengan segera akan bergegas mengikuti Sang Guru. Sebuah ajakan yang amat persuasif, ajakan yang penuh persahabatan, ajakan yang tidak membuat tembok pemisah: Anda murid, saya guru, tetapi ajakan yang meleburkan saling hormat dan rasa segan (bukan karena takut) karena Sang Guru menjawab dengan membuka tangan dan mempersilakan murid masuk ke kehidupan pribadinya. Mari dan Lihatlah. Ajakan imperatif namun egaliter. Karena di sana mereka akan duduk bersama untuk mengada sebagai pemberi jawab (guru) melalui tindakan dan tutur kata dan sebagai penerima jawab (murid)
BERUSAHA UNTUK HADIR
Sudah empat bulan ini saya mengajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebuah atribut yang berat untuk disandang. Karena menyangkut dua hal. Pertama pendidikan agama dan kedua budi pekerti. Pendidikan agama tentu saja bukan soal pengetahuan kognitif tentang agama, tetapi bagaimana seorang guru menghidupi pengetahuan agamanya itu di hadapan para muridnya. Sedangkan budi pekerti menyangkut etika hidup yang bersesuaian dengan pendidikan agama yang diterimakan kepada para murid. Sebelum mengajari muridnya tentang budi pekerti, seorang guru mesti memberikan teladan hidup yang bepekerti itu seperti apa, supaya dia tidak hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa menghidupi apa yang dibicarakannya.
Tuntutan kurikulum 13 dan merdeka belajar (ada sekolah yang masih menjalankan dua kurikulum ini sekaligus karena K13 belum selesai), guru hadir sebagai pemicu dan pemacu pengetahuan bagi siswa. Guru bukan seorang yang memonopoli semua pengetahuan dari A sampai Z. Apalagi menyangkut pendidikan agama dan budi pekerti.
Saya selalu membiasakan kepada para siswa untuk bercerita tentang pengalaman selama seminggu yang telah lewat. Apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang direfleksikan atas pengalaman-pengalaman itu. Hal itu dibangun untuk menciptakan kedekatan antara guru dan murid. Tentu saya juga bercerita apa yang saya alami dan refleksikan sehingga para murid saya menemukan contoh bagaimana sebuah pengalaman itu diolah sehingga menjadi bagian dari diri yang amat bernilai, sekecil dan sesederhana apapun pengalaman itu.
Duduk bersama dan saling berbagi tentang agama (katekese dan pastoral) lebih menyapa orang muda daripada kita sibuk “menjejali” para murid dengan pengetahuan sesuai dengan buku panduan atau tujuan dan target yang disusun oleh para pembuat buku ajar (yang seolah-olah itulah yang paling dibutuhkan oleh siswa) tentang agama dan budi pekerti. Mengajar dengan teladan selalu lebih hidup dan manusiawi. Dari situlah muncul kecintaan para siswa terhadap sesuatu yang akan dipelajarinya.
Tentu saja, sebagai guru agama katolik, hal-hal dasariah sebagai seorang katolik (seperti bagaimana membuat tanda salib yang benar, berdoa dengan sikap yang benar, bagaimana menyusun sebuah doa, itu lebih penting untuk kehidupannya nanti) ketimbang mengajari yang rumit soal apa itu agama katolik menurut ajaran Gereja, Kitab Suci dan Tradisi. Secara kognitif ketiga hal itu perlu dan penting, tetapi karakter sebagai seorang katolik jauh lebih utama karena itulah yang akan dibawa seumur hidupnya.
MENGHIDUPI “SPIRITUALITAS” KI HAJAR DEWANTARA
Spiritualitas pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara selalu aktual dalam sistem pendidikan kita baik secara formal di sekolah maupun informal di rumah atau tempat lain. “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang artinya Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik, di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan/dukungan dan arahan,” diyakini masih amat relevan. Bagaimana guru-guru memaknai ketiga kalimat di atas dalam konteks kekinian di hadapan generasi milenial (Gen Z) yang hari-harinya “makan” teknologi digital?
Ketiga kata-kata mantra Ki Hajar di atas menuntut seorang guru untuk tidak pandai bicara saja dari depan kelas, membuat kalimat-kalimat imperatif yang hanya boleh dilakukan oleh siswanya. Guru mesti pertama-tama menghidupi omongannya dan konsisten merawat dan menghidupinya sepanjang hayatnya sebagai seorang guru. Di sanalah ada rasa hormat sekalipun kedekatannya dengan para murid seakan tak bersekat, duduk sejajar, berjalan beriringan.
Jika kementerian pendidikan dan seluruh stakeholder konsisten untuk merawat dan menghidupi ketiga mantra atau spiritualitas pendidikan model Ki Hajar di atas, maka tidak akan terjadi uji coba kurikulum yang terus silih berganti seperti cendawan di musim hujan atau sebuah proyek yang tampak mulia bagi para siswa tetapi justru membelenggu guru dan siswanya. Nama kurikulum makin sering terjadi, justru seharusnya kualitas Pendidikan Indonesia tidak akan menempati urutan 67 dunia.
Semoga peringatan hari Guru setiap tanggal 25 November tidak hanya seremonial belaka atau tidak sekadar proyek para pemangku kebijakan terkait untuk uji coba kurikulum saban periode. Terlepas dari kegundahan di atas, para guru (yang sering menjadi korban sistem) patutlah mendapatkan apresiasi. Selamat Hari Guru.
Kaki Merapi, 25 November 2023